Sebagaian orang mungkin merasa aneh
kenapa seorang-saya menganggap demokrasi tidak cocok dengan agama. Saya bilang
agama, bukan agama saya saja. Bahkan saya berani berpendapat bahwa demokrasi
itu memang dikonsep untuk melawan agama.
Bagi saya, agama adalah aturan
tertua. Apa yang disebut kearifan lokal, norma, dan adat istiadat pun,
sumbernya adalah agama. Logika ini sangat sederhana. Berhubung agama itu
jalan yang dibuat oleh Tuhan, lalu
apakah ada yang lebih awal dari Tuhan?
Makna paling mendasar dari demokrasi
adalah aturan yang sesuai kehendak mayoritas. Segala atribut-atribut lain yang
disematkan padanya tak lain hanyalah hiasan dan harapan akan sebuah keadaan.
Contoh-contoh atribut lain itu diantaranya: kesamaan hak, kebebasan
berpendapat, transparansi, atau trias-politica. Padahal, dengan makna demokrasi
yang mendasar dan sederhana tadi, kalau mayoritas berkehendak bahwa golongan
tertentu haknya lebih, ya itu tetap demokrasi. Atau kalau mayoritas berkehendak
tidak ada kebebasan berpendapat, ya itu juga demokrasi, begitu seterusnya.
Pokoknya tidak ada ciri lain selain aturan sesuai kehendak mayoritas. Sebanyak
apapun telur, ayam goreng, perkedel, dan brokoli, Indomie tetap hanya yang ada
di dalam bungkusnya saja. Lainnya, tambahan. Tak bisa kita katakan bahwa ayam
goreng atau brokoli adalah Indomie. Bagi yang tidak suka Indomie, silakan ganti
dengan Supermi, Sarimi, Mie Sedap, atau Mie Sukses isi dua.
Nah, dalam titik inilah demokrasi
terlihat bukan hanya tidak cocok dengan agama, tapi juga bermusuhan. Jika agama bicara tentang ‘harus’, demokrasi
bicara tentang ‘tergantung’. Jika agama bicara tentang hal-hal tertentu saja manusia
boleh menentukan, maka demokrasi menganggap bisa semuanya. Memang canggung
untuk langsung mengatakan demokrasi sebuah keburukan, melainkah sesuatau yang
berlebihan. Sesuatu yang berlebihan pasti buruk. Nah, tak lagi canggung.
Demokrasi memang sebuah konsep
pembablasan akan otoritas tunggal. Maka, tak ayal, beberapa orang menganggp
bahwa demokrasi adalah berhala. Buat saya, itu tidak lebay. Setidaknya sebuah
kisah di bawah ini bisa menjadi contoh bahwa kehendak mayoritas bisa menjadi jalan menuju pemberhalaan,
sekalipun di dalam masyarakat yang punya tradisi mengesakan Tuhan.
Atas perintah Allah, Musa menuju
bukit Thur untuk menerima mukjizat Taurat. Musa berencana pergi selama 10
malam, tapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa
pun menitipkan Bani Israil pada adiknya, Nabi Harun. "Gantikanlah aku
dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan
orang-orang yang membuat kerusakan," ujar Musa.
Harun pun kemudian memimpin Bani Israil. Namun, rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun. Ia pun mengajak Bani Israil untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir. "Jadilah anak sapi!" teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Lupa sudah Samiri akan peringatan Musa agar tak menyembah berhala, tapi selalu mengesakan Allah.
Dengan kebodohan Bani Israil, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi. Sementara, Harun tak sanggup melawan Bani Israil sendirian. (dari Republika online)
Harun pun kemudian memimpin Bani Israil. Namun, rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun. Ia pun mengajak Bani Israil untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir. "Jadilah anak sapi!" teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Lupa sudah Samiri akan peringatan Musa agar tak menyembah berhala, tapi selalu mengesakan Allah.
Dengan kebodohan Bani Israil, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi. Sementara, Harun tak sanggup melawan Bani Israil sendirian. (dari Republika online)
Jangankan ulama atau pemuka agama, rasul
yang masih hidup saja bisa ditentang oleh mayoritas yang menggunakan konsep ini.
Bayangkan! Dosa terberat, menyekutukan Tuhan saja bisa lolos, apalagi maksiat
lainnya. Karena yang penting itu kehendak mayoritas, tak ada urusan sekalipun dengan
utusan Tuhan. Jadi, tak lebay kan, jika demokrasi dianggap berhala?
Demokrasi memang disepakati untuk
menentang otoritas tunggal. Baik Tuhan, apalagi sekadar rasul, terlebih raja
dan ratu. Apa yang wajib bisa jadi pilihan, bahkan malah jadi terlarang, selama
mayoritas menghendaki demikian. Sebaliknya, sesuatu yang terlarang bisa jadi
boleh, bahkan wajib asal mayoritas menghendaki. Tak heran, di sebuah negara dengan
jumlah penduduk muslim terbanyak, dengan banyaknya ahli agama, majelis ilmu,
sampai majelis ulama, mengamalkan maksiat yang dosanya bekali-kali lipat dari
dosa menzinah ibu kandung, menjadi hal biasa. Gimana kurang musuhan dengan
agama coba?
Tak heran, di negara-negara yang
berhasil demokrasinya, ya pasti berhasil sekuler dan liberalnya. Judi jadi
industri. Zinah jadi industri. Mabok jadi industri. Riba jadi industri. Kalau
belum begini, ya belum berhasil demokrasinya. Negara-negara yang jajal fusion
antara agama dan demokrasi akan selalu jadi negara bimbang, labil, dan ngambang
kayak ‘itu’ di empang. Terombang-ambilng gelombang air karena tiupan angin.
Jadilah banyak aturan banci, yang memang setengah-agama-setengah-liberal,
setengah-taat-setengah-maksiat. Mau liberal terganjal agama, mau taat terganjal
selera massa.
Untungnya, itu bukan sebuah arti kesuksesan.
Bagi saya, sukses itu kalau kita berhasil cukup tanpa menentang falsafah hidup
tertinggi. Jadi, negara dengan industri maksiat, bisa jadi kaya, megah,
berlimpah, tapi dia tidak sukses. Kekayaannya pasti tidak menjadi berkah baginya
dan bagi tetangganya. Tak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terbayang nggak,
timpangnya Amerika dengan Afrika?
Tapi
demokrasi banyak menghasilkan aturan yang baik, loh.
Kebaikan itu sudah default
settingnya agama untuk manusia. Tuhan selalu membolehkan, bahkan mewajibkan kebaikan. Demokrasi
itu versi telat-klaimnya kebaikan hidup.
Nah, baru dah saya sambung-sambungin
ke hal aktual kekinian yang sedang hangat-hangatnya, bahkan panas-panasnya,
karena berhasil membuaskan banyak orang. Tentang bagaimana perhelatan demokrasi
dalam memilih kepala daerah yang menjadi ibu kota Indonesia gitu ganti.
Bagimana dalil agama dijadikan pertimbangan untuk tidak memilih salah satu
calon, karena calonnya: Kafir. Calonnya tidak seagama. Dalil ini wajar saja
jika ada dalam agama lain.
Masalahnya, dalil ini bisa dianggap berlebihan
dari sudut pandang demokrasi aktual. Muslim vs Kafir. Orang muslim haram memiih
orang kafir! Itu benar. Tapi kalau mayoritas orang muslimnya memilih demokrasi,
yang salah satu hasilnya, dengan kehendak mayoritas, membolehkan orang kafir
jadi pemimpin, ya itu resiko. Kalau kamu memilih iPhone, ya terima lambang
apelnya yang sudah terbelah, jangan minta diservice supaya apelnya utuh.
“Bang, ada iphone 11S yang apelnya
masih utuh nggak?”
Abang-abang iBox langsung resign.
Ya, tapi kan memilih orang kafir itu
haram! Dosa!
Yah, dia sekarang bicara dosa.
Memang demokrasi dikonsep untuk apa? Untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala?
Untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan? Baca lagi dari awal
mendingan.
Bagi saya, yang patut disyukuri
dalam hidup ini, terkait keberadaan konsep demokrasi dalam hidup ini, adalah
bahwa, demokrasi bukan syarat bernegara.
Lebih bersyukur lagi, demokrasi bukanlah syarat menjadi manusia. Sangat bersyukur
lagi demokrasi bukan syarat untku bisa memberi dan menerima cinta. Paling
besyukur lagi, demokrasi bukan syarat untuk bisa masuk surga, yang semoga kita
berada di sana bersama-sama nantinya.
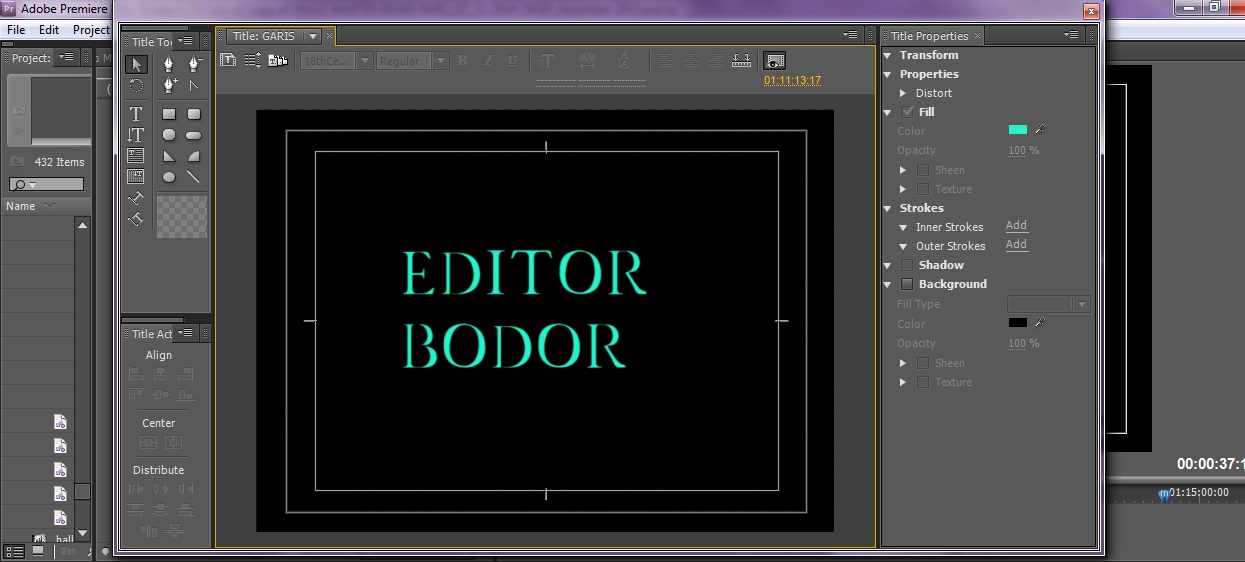
Tidak ada komentar:
Posting Komentar