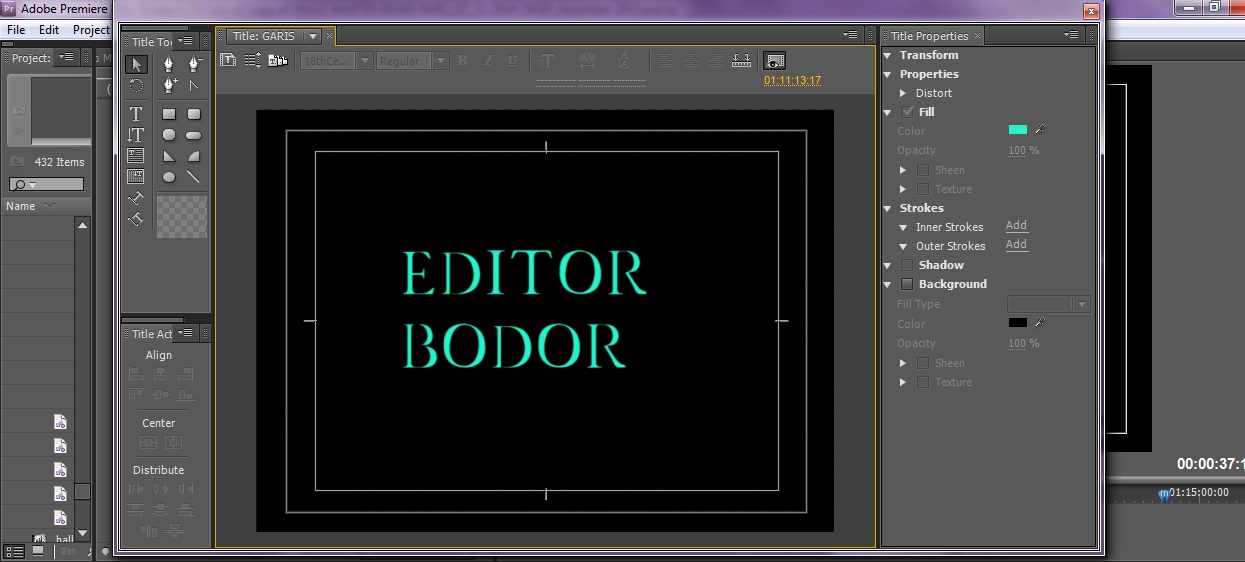Selasa, 19 April 2016
Cerpen: Ujung Hutan
Wira tak mampu menutupi rasa malunya. Hanya duduk menunduk di tengah balai sidang. Dadanya disesaki oleh sesal. Ia merasa semua mata mentap dengan benci, kecuali, mungkin, kedua orang tuanya.
Hampir semua warga desa hadir dalam sidang. Para tetua, pemuda, sampai anak-anak. Mereka yang tak kebagian duduk di kursi kayu, duduk di anak tangga, di setiap sisi balai yang beratap, berubin, namun tak berdinding itu. Dalam sidang ini, bahkan anak-anak tak ada yang berani bercanda. Semua orang menutup mulut, kecuali mereka yang berhak bersuara.
“Wira melakukan dosa besar! Ia telah mencuri!” kata Abah Una sambil menujuk Wira. Sorot matanya tajam wujud ketegasan.
Ayah Wira menggeleng. “Anakku bukan mencuri, Abah Una! Dia hanya membawa apa yang tertinggal dari mahasiswa yang melintasi desa.”
“Membawa masuk barang milik orang lain saja sudah sebuah kesalahan, Kuswan!” ujar Abah Una. “Bisa saja itu adalah barang yang berbahaya!”
Suasana jadi berisik karena warga saling bisik. Mereka menyadari bahaya besar akibat perbuatan Wira. Sudah banyak mahasiswa atau polisi hutan melintas desa selama ini. Tak ada satu pun yang berulah. Perbuaatan Wira bisa mengubah segalanya.
Berisiknya warga membuat wajah Wira semakin merah. Ia tak mampu melihat wajah orang-orang, terlebih lagi orang tuanya. Ia yakin ibunya sedang menahan tangis, atau bakan amarah.
Ki Agum tiba-tiba berkata dengan wibawa. “Coba tunjukan benda yang dibawa Wira.” pintanya dengan sopan. Salah seorang pemuda bangun, memberikan benda itu pada Ki Agum. Semua mata ikut melihat. Benda itu kotak, biru, cukup kecil untuk bisa digenggam, dan tesambung dengan rantai kecil yang menggantung.
“Ada yang tahu nama dan guna benda ini?” tanya Ki Agum sambil melihat sekeliling. Tak ada yang menjawab, hanya menggeleng.
“Jika kita tidak tahu guna benda itu, bagaimana kita menganggapnya berbahaya?”, ujar Kang Kuswan, membela anaknya.
“Justru, karena kita tidak tahu, bagaimana kita menganggapnya tidak berbahaya?” balas Abah Una dengan sinis. Wira bisa melihat dengan lirikan, banyak orang mengangguk, lebih percaya pada perkataan Abah Una ketimbang ayahnya.
“Kita tidak mungkin menganggap tindakan Wira bukan kesalahan, karena tak ada benda asing yang boleh masuk ke desa kita.” kata Ki Agum. “Kita hanya bisa memutuskan kadar kesalahannya.”. Keringat Wira mulai keluar dari samping kepalanya, membayangkan dirinya sampai menjalani hukuman berat. Kesalahan besar berarti hukuman berat.
“Malam ini juga, hukuman akan diputuskan oleh para sesepuh.”, tambah Ki Agum. Kedua tangannya memberi isyarat agar para sesepuh lain mendekat padanya. Sepuluh sesepuh lain, termasuk Kang Kuswan dan Abah Una menuruti isyarat Ki Agum. Mereka setengah berbisik memberi suara. Semua warga desa berusaha mencuri dengar.
Ki Agum melangkah lebih depan dari sesepuh lain. “Ringan.” ucapnya tegas. “Wira kami jatuhi hukuman mengurus kebun desa selama satu bulan. Semoga Wira tidak meremehkan kesalahannya. Dan ini menjadi pelajaran bagi warga yang lain.”
Ucapan itu membuat para sesepuh membubarkan diri dalam iringan keriuhan suara warga. Beberapa warga mengangguk, beberapa menggeleng, setelah mendengar keputusan itu. Abah Una melangkah dengan cepat dengan raut kecewa.
Kang Kuswan dan Nyai Diah mendekati anaknya yang masih menunduk. Wira tak bisa menahan diri untuk tidak memeluk ayahnya sebagai ganti terima kasih.
“Berjanjilah kamu tak akan melakukan itu lagi.” sambung Kang Kuswan, sangat dekat dengan telinga anaknya. “Aku berjanji, ayah!” ucap Wira tegas. Ia sangat tahu, tak boleh ada lagi penasaran terhadap benda asing milik orang lain dari luar desa.
Malam itu adalah tidur nyanyak pertama Wira sejak seorang anak memergokinya membawa benda kotak berwarna biru. Benda yang hampir saja membuatnya dalam bahaya besar.
Tiga hari sudah Wira melaksanakan hukuman. Seorang diri menggarap kebun desa. Hukuman yang membuat warga lainnya punya waktu berlibur bersama keluarga. Meski sendiri, semua terasa ringan jika ia membayangkan hukuman berat yang hampir menimpanya.
Wira tak lagi sendiri. Seseorang datang dari balik pepohonan. “WIRA!”, teriak sesorang lelaki dari kejauhan, membuat burung-burung di pepohonan beterbangan. Wira mendekat, tahu bahwa itu adalah Surya, teman sebayanya.
“Ada apa?” tanya Wira penasaran. Surya tak langsung menjawab. Ia memberi tatapan sinyal keprihatinan. “Ada apa?” ulang Wira lebih keras.
“Kamu ditunggu di balai warga.”, jawab Surya.
“Memang ada apa?”
Surya hanya menggeleng meski tahu. Dan ia tetap tak mau menjawab sepajang perjalanan. Wira malah mendapati kerumunan orang di sekitar balai sidang. Ia tak mampu menebak apa yang akan menimpa meski telah sampai ke desa. Wira masuk ke balai sidang, melewati orang-orang yang menatap sinis.
Balai sidang lebih ramai dari sidang lalu. Wira melihat mata ibunya yang sembab dan basah. Ayahnya bahkan tidak mau melihat ia melintas. Abah Una membalik tubuhnya ketika tahu Wira sudah tiba. Ia menatap Wira tanpa belas kasih.
“Aku sudah tahu benda yang kau bawa ini!” Abah Una setengah berteriak. “Biar pamong praja perbatasan ini yang mengatakan!” sambil menunjuk pada orang yang berdiri di samping Abah Una. Orang itu melihat sekeliling sebelum bicara, memastikan semua orang siap mendengarnya.
“Aku membawa benda itu ke perbatasan.” ucapnya lantang. “Aku menyamar agar bisa bertanya pada Polisi Hutan.”. Ucapan yang membuat warga desa berdesas-desus seketika.
“Polisi Hutan mengatakan bahwa benda itu bernama Ji Pi Es.” Sambung Si Pamong Praja. “Benda yang berguna sebagai peta. Benda yang bisa diketahui keberadaannya dari jarak yang sangat jauh.”
Bisik-bisik warga menjadi riuh seketika. Wira tiba-tiba merasa mual. Ia merasa badannya seperti mengkerut sekaligus lemas. Para sesepuh saling bicara, dan sesekali melihat ke arahnya. Ayahnya hanya diam seribu bahasa.
“Mohon tenang!” Ki Agum menghentikan keriuhan warga. Suara paling tinggi dari Ki Agum yang pernah Wira dengar selama ini. Ia tahu bahwa ada kemarahan dalam suaranya.
“Kami memutuskan untuk mengubah hukuman bagi Wira.”, katanya dengan tegas. “Ini akan menjadi pelajaran bagi semua warga.”
Suasana semakin riuh. Ki Agum memberi isyarat tangan agar semua berhenti bicara.
“Hukuman berat akan dijatuhkan.” ujar Ki Agum sambil memandang Wira. Pandangannya seperti meminta pemakluman akan ketegasan yang harus ia lakukan. Tangan Ki Agum menjulur dengan isyarat menunjuk ke arah luar balai warga, lalu berkata “Wira Diasingkan selama satu bulan!”
Meski Wira tahu itu akan terucap, tetap saja membuatnya sesak. Wira tahu bahwa diasingkan berarti keluar dari desa, segera setelah Ki Agum memberi isyarat pengusiran dengan telunjuknya.
“Pamong Praja akan mengantar sampai perbatasan, untuk memastikan kamu menjalankan hukuman dengan benar.” kata Ki Agum sambil melangkah keluar balai sidang. Itu sekaligus isyarat agar Wira segera melangkah meninggalkan balai, juga desa.
Wira tahu langkah para sesepuh dan warga menggiring langkahnya. Ia bisa mendengar beberapa ibu yang mengelus-elus anaknya sambil menasihati agar tidak bernasib sama dengan dirinya.
“Aku akan ikut mengantarmu sampai ujung hutan, Wira.”, ujar Surya yang mengikuti. Wira senang mengetahui Surya mau melakukan itu, meski ia berharap ayahnya yang akan mengantar ke perbatasan.
“Apa kamu yakin?”, tanya Wira menoleh ke belakang tanpa berhenti. “Ujung hutan itu sangat jauh.”
“Ya, aku yakin.”, jawab Surya. “Lagi pula, sudah lama aku tak ke sana.”
Wira tersenyum secukupnya. Kebaikan Surya cukup menghibur. Wira, Surya, dan Si Pamong Praja terus berjalan hingga melewati rumah terakhir. Mereka mulai menapak di jalan setapak.
“Wira!”, panggil ayahnya dari belakang punggung. “Ayah akan ikut mengantarmu.”, kata ayahnya, menyusul Pamong Praja dan Surya, menyamai kecepatan Wira. “Makanlah ini, Nak!”. Ayahnya memberi nasi lalap yang dibungkus daun pisang. “Aku tak mau makan sendirian.”, kata Wira, menahan diri, meski ia sempat melirik bungkusan itu.
“Makanlah dulu, Nak!”, Si Pamong Praja memberi saran. Surya mengangguk memberi dukungan. Kang Kuswan kembali menyodorkan. “Kami akan kembali ke desa setelah ini. Sedangkan kau mungkin harus berburu, memakan daging mentah di luar sana.”, Kang Kuswan memberi pengertian. “Kamu akan sangat membutuhkan tenaga.”
Wira kembali melirik bungkusan lalu berhenti. Ia menerima makanan itu dari ayahnya. Wira menduduki tonjolan akar pohon pada pinggiran jalan setapak untuk makan. Itu adalah makan siang terlambatnya, dan mungkin sekaligus makan malam. Wira memakan semua dengan lahap.
“Ingatlah nak, kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan polisi hutan.” Ucap Kang Kuswa. “Mereka tidak akan melukaimu, karena mereka bertugas melindungi desa kita, meski secara tak langsung.”
Wira mengangguk-ngangguk sambil terus mengunyah. “Aku akan baik-baik saja, ayah.” tanggap Wira, lebih kepada usaha membuat ayahnya tidak khawatir. Ia tak ingin membebani lebih banyak lagi, meski tahu akan berada dalam bahaya.
Wira sudah membersihkan tangannya dari semua nasi yang menempel di jari tangan kanan. Keempatnya kembali berjalan. Tak ada lagi perhentian. Jalan setapak mulai menurun. Ujung hutan sudah terlihat.
Si Pamong Praja paling dulu mengehentikan langkahnya. Ia tidak mau lebih dekat lagi dengan perbatasan, namun terus mengikuti Wira dengan matanya.
“Jangan mudah marah jika melihat orang menebang pohon.”, kata Si Pamong Praja dari balik punggung Wira. “Mereka yang dari Perhutani, juga para polisi hutan, sudah punya perhitungan yang matang dalam menebang, agar hutan tetap lestari.”
Wira mengangguk. Ia sudah mendengar hal itu dari sesepuh desa. Juga tentang orang-orang Perhutani yang tahu akan keberadaan desanya. Kabarnya, mereka sangat menghormati keberadaan warga, meski tak semua dari mereka percaya.
Langkah Surya juga sudah berhenti. Wira bersiap kehilangan derap langkah sang ayah. Jantungnya semakin berdebar. Sulit baginya meninggalkan hutan di belakang. Berat baginya meninggalkan desa. Ia tak pernah mengerti, kenapa manusia bisa hidup begitu jauh dari hutan. Jauh dari kesejukan, keteduhan, dan suara satwa di dalamnya.
Suara langkah ayah sudah punah. Sekarang tinggal langkah kakinya. Wira menoleh, melihat tiga orang pengantarnya. Ayahnya menunduk, Surya pun demikian. Hanya Si Pamong Praja yang bertatap muka dari gundukan jalan setapak. Tatapan kewajiban, memastikan Wira melaksanakan pengasingan dengan wujud yang semestinya.
Wira berpaling, melangkah lagi menuju ujung hutan. Jalannya mulai membungkuk. Wujudnya mulai berganti. Ia tak mengira akan mengalaminya dua kali. Menjelma seperti pertama kali ia masuk ke dalam hutan. Ketika itu, ia memilih ikut bersama rombongan yang setia pada Kakang Prabu. Ia berharap kabar kesalahannya tidak sampai ke telinga rajanya itu, karena ia sangat malu.
=======
Cerpen ini menjadi juara III Kategori-C Lomba Menulis cerpen Green Pen Award 2016 yang diselenggarakan oleh Perum Perhutani.
Langganan:
Postingan (Atom)